KETIKA ETIKA DIKESAMPINGKAN: NORMALISASI RANGKAP JABATAN SEBAGAI BUDAYA BARU DALAM BIROKRASI
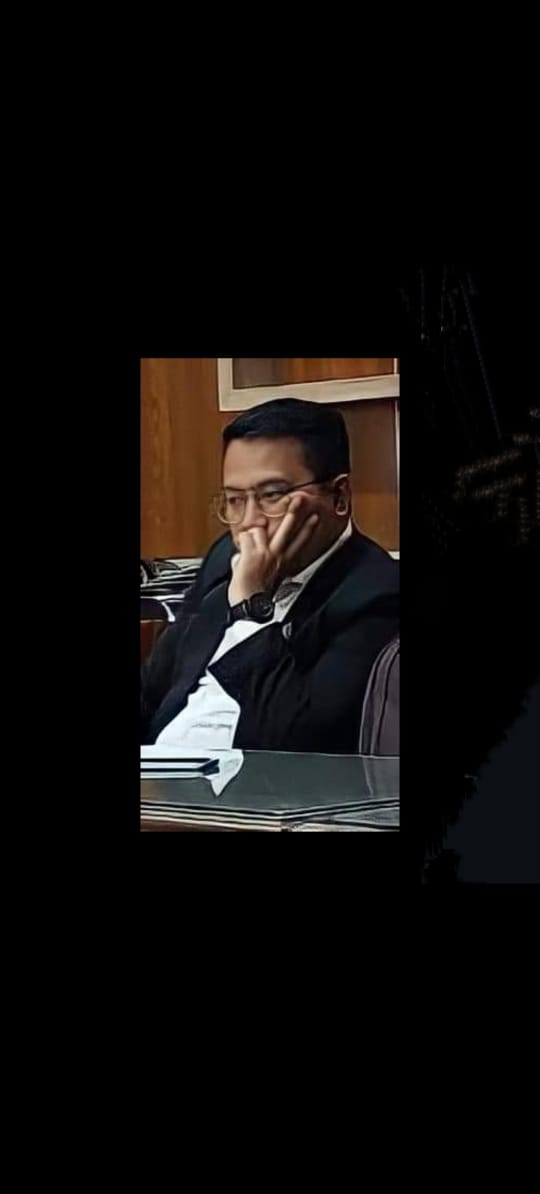
oleh : Dr. Muzwar Irawan.SH.,MH
(Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sari Mutiara Indonesia)
Menelisik kondisi sekarang, sangat relevan rasanya untuk merenungkan pandangan
Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 1968 hingga 1971. Beliau pernah berkata “Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari atas. Seperti halnya orang mandi, guyuran air untuk membersihkan diri selalu dimulai dari kepala.” Dikesempatan lain, beliau juga mengingatkan “Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.”
Fenomena rangkap jabatan, telah berubah dari sekedar anomali birokratis menjadi penyakit sistematik dalam tata kelola pemerintah di Indonesia, hal ini menunjukkan kecendrungan kekhawatiran publik, yaitu tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi bisa meluas ke berbagai daerah dan sektor lainnya, termasuk ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta organisasi semi publik lainnya. Praktik dominasi rangkap jabatan sejatinya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menurunnya efektivitas publik, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pun perlahan akan terpinggirkan demi kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan individu yang pragmatis.
Padahal, larangan rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif negara sebenarnya telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya tercantum dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris maupun direksi pada perusahaan negara ataupun swasta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada publik. “Pasal ini terang benderang, tidak multitafsir. Karena jabatan wakil menteri adalah bagian dari struktur kementerian dan pembantu presiden, maka semestinya terikat pula pada semangat dan norma dalam undang-undang ini”.
Selain itu, didalam Pasal 17 huruf A Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan, “Pelaksana dilarang: a.merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah” dimana melarang pelaksana pelayanan publik dari instansi pemerintah merangkap jabatan di organisasi usaha. Lebih lanjut, didalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara khusus menekankan larangan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan.
Lebih lanjut, mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mempertegas bahwa semangat konstitusi kita tidak pernah membenarkan penumpukan kekuasaan administratif dan korporatif dalam satu tangan (larangan menteri dan wakil mentteri sama sama ditunjuk oleh Presiden sehingga memiliki status yang sama). Kalau pejabat public dalam pembahasan ini terkait para wakil mentri (wamen) yang lagi marak rangkap jabatan, maka bisa dikatakan “inkonstitusonal” bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.
Selanjutnya dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: (a) pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun perusahaan swasta; serta (c) pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini menjadi dasar hukum (legal standing) bagi para Wakil Menteri dimaksud, mengapa mereka diangkat, tujuannya agar fokus menanggapi beban kerja di masing masing kementerian karena yang merlukan perhatian khusus dan secara lebih optimal.
Nah, apabila rangkap jabatan ini terus dibiarkan, akan menjadi menuai sorotan publik terkait efektifitas kinerja dan berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Bahkan, melemahkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, sepanjang konflik kepentingan tidak dicegah bisa menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga bakal merugikan banyak pihak.
Menjaga Marwah Reformasi BUMN: Antara Regulasi dan Realitas
Terakhir, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan langkah strategis dalam mereformasi tata kelola BUMN agar lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah pembatasan peran negara hanya sebagai pemegang saham, tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan operasional. Tujuannya tidak lain adalah menciptakan iklim bisnis yang lebih independen, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika pasar, baik ditingkat nasional maupun global.
Namun dalam pengimplementasinya masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Pasal 28 misalnya, secara tegas mewajibkan para komisaris BUMN menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara maksimal. Sayangnya, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Banyak komisaris justru berasal dari kalangan pejabat aktif yang sudah dibebani dengan tanggung jawab utamanya. Kondisi ini jelas kontraproduktif, sebab peran komisaris bukan sekadar posisi simbolis, melainkan elemen penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis di tubuh BUMN.
Akan menjadi ironis, efektivitas dan independensi pejabat yang seharusnya mengawasi justru menerima kompensasi dari entitas yang diawasi. Maka muncul pertanyaan yang sangat mendasar: bagaimana mungkin pengawasan dapat berjalan independen jika hubungan keuangan telah menciptakan ketergantungan? Potensi benturan kepentingan bukan hanya ancaman etis, tetapi juga menjadi hambatan nyata dalam membangun akuntabilitas dan transparansi di tubuh BUMN. Indonesia tidak pernah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan independen. Berikan kesempatan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk itu, berdasarkan keahlian dan kemampuannya untuk mengisi di posisi strategis seperti komisaris merupakan progresif untuk membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih sehat, transparan dan berintegritas, sehingga terciptalah “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam PANCASILA.
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 secara tegas melarang rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, termasuk sebagai anggota Direksi di BUMN, BUMD atau perusahaan swasta. Ketentuan ini seharusnya ditegakkan secara konsisten dan tidak menjadi aturan formalitas semata. Dengan demikian, semangat reformasi BUMN tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam praktik. Penguatan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan komisaris adalah langkah nyata menuju tata kelola BUMN yang lebih baik demi kepentingan publik dan pembangunan nasional. Sayangnya, di tengah upaya perbaikan sistemik, publik patut mempertanyakan alasan di balik penghapusan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Apakah penghapusan ini mencerminkan kemunduran dalam komitmen terhadap prinsip Good Corporate Governance? Apakah kepentingan efisiensi dan profesionalisme kini kembali dikalahkan oleh akomodasi politik dan kompromi jabatan? Jika larangan rangkap jabatan dianggap tidak lagi relevan, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel. Diskursus ini penting untuk dibuka secara luas agar masyarakat dapat menilai: apakah reformasi BUMN benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat, atau hanya menjadi alat konsolidasi kekuasaan di ruang-ruang strategis ekonomi negara?


